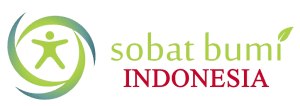Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang merupakan waduk yang terdapat di Provinsi Riau. Waduk Koto Panjang ini merupakan hasil pembendungan beberapa sungai, yaitu Sungai Kampar Kanan, Batang Mahat, Gulamo, Tapung Air Tiris, Kapau Batang Mahat, Gulamo, Tapung Air Tiris, Kapau, Tiwi, Takus, Osang, Arau Kecil, Arau Besar, dan Cunding di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas genangan sekitar 12.400 ha. Sungai Kampar Kanan merupakan sungai utama yang mengalir menuju waduk PLTA Koto Panjang sebagai inlet yang berhulu di Sumatera Barat. Fungsi utama waduk ini adalah sebagai pembangkit listrik dan pengendali banjir.
Di sekitar perairan Waduk PLTA Koto Panjang terdapat aktivitas seperti pemukiman dan perkebunan, sedangkan di waduknya sendiri terdapat kegiatan Keramba Jaring Apung (KJA) dan pemancingan. Adakalanya waduk ini digunakan untuk persinggahan perjalanan karena berada di jalan lintas Sumatera Barat dan Riau. Peningkatan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pemukiman, serta penebangan hutan telah menyebabkan penurunan kualitas perairan waduk, yaitu sedimentasi dan eutrofikasi yang merupakan hasil akumulasi bahan organik yang terbawa oleh aliran sungai atau aliran permukaan ke dalam waduk. Perubahan kondisi kualitas perairan pada aliran sungai merupakan dampak kegiatan penggunaan lahan yang ada disekitar sungai (Tafangenyasa & Dzinomwa 2005).
Eutrofikasi merupakan masalah yang dihadapi seluruh dunia yang terjadi dalam ekosistem perairan tawar maupun laut. Eutrofikasi merupakan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan kadar nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, di perairan. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, menciptakan kondisi perairan yang tidak sehat dan dapat merugikan ekosistem. Peningkatan kesuburan yang terus-menerus pada perairan dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan fungsi waduk, pendangkalan, penurunan kualitas perairan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup biota yang mendiami perairan Waduk PLTA Koto Panjang.
Tingginya bahan organik pada perairan waduk diperoleh dari buangan limbah pertanian, perumahan, industri, dan sisa pakan dari KJA. memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Alga ini kemudian mengalami peningkatan populasi secara cepat, membentuk alga toksik atau bloom alga. Ini dapat menghambat sirkulasi air dan mengurangi kadar oksigen, yang dapat membahayakan kehidupan akuatik.
Status perairan Waduk PLTA Koto Panjang termasuk kategori tercemar, sedang, hingga tercemar berat, semakin ke daerah outlet perairan waduk semakin tercemar. Ada beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu perairan adalah amonia, nitrit, fosfor, dan BOD5. Sedangkan fecal coliform masih dalam kategori yang baik. Status kesuburan Waduk PLTA Koto Panjang secara umum dilihat dari nilai rata-rata TLI termasuk dalam kategori supertrofik hingga hipertrofik.
Lalu, bagaimana caranya mengatasi eutrofikasi?
Salah satu cara untuk mengatasi eutrofikasi adalah dengan menggunakan hidrogen peroksida (H2O2), suatu senyawa yang dapat menghasilkan oksigen dan membantu mengurangi kadar nutrien dalam perairan
Pertama-tama, penting untuk memahami bagaimana eutrofikasi terjadi. Biasanya, nutrien dari limbah pertanian, industri, atau limbah domestik masuk ke perairan, memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Alga ini kemudian mengalami peningkatan populasi secara cepat, membentuk alga toksik atau bloom alga. Ini dapat menghambat sirkulasi air dan mengurangi kadar oksigen, yang dapat membahayakan kehidupan akuatik.
Hidrogen peroksida sendiri adalah oksidator yang kuat dan dapat diuraikan menjadi air (H2O) dan oksigen (O2). Penggunaan hidrogen peroksida dalam konsentrasi yang tepat dapat membantu mengoksidasi nutrien yang berlebihan, seperti fosfat, dalam air. Oksidasi ini mengurangi ketersediaan nutrien bagi alga dan menghambat pertumbuhannya.
Selain itu, hidrogen peroksida dapat digunakan untuk mengurangi keberadaan alga yang telah tumbuh berlebihan. Dengan aplikasi yang tepat, hidrogen peroksida dapat merusak membran sel alga dan menghambat fotosintesisnya. Hal ini membantu mengendalikan populasi alga dan mengembalikan keseimbangan ekosistem perairan. Namun, penting untuk mencatat bahwa penggunaan hidrogen peroksida harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan dampaknya pada ekosistem. Konsentrasi hidrogen peroksida yang terlalu tinggi dapat merugikan organisme akuatik yang diinginkan dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi yang cermat untuk menentukan dosis yang optimal dan metode aplikasi yang tepat sesuai dengan kondisi spesifik perairan yang terkena eutrofikasi.
Apakah ada cara lain?
Selain penggunaan hidrogen peroksida, pendekatan terhadap eutrofikasi juga harus mencakup upaya pencegahan. Ini termasuk pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan pupuk, dan perlindungan vegetasi riparian. Kombinasi dari berbagai strategi ini dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan terhadap permasalahan eutrofikasi.
Dalam pengembangan solusi untuk eutrofikasi, keterlibatan komunitas lokal, pemerintah, dan ahli lingkungan sangat penting. Edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah dan pentingnya pelestarian sumber daya air juga merupakan langkah kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan. dengan demikian, penggunaan hidrogen peroksida sebagai bagian dari strategi pengendalian eutrofikasi dapat menjadi solusi yang efektif, tetapi perlu diintegrasikan dengan upaya pencegahan dan pengelolaan yang komprehensif. Melalui pendekatan yang berimbang dan kolaboratif, kita dapat mencapai perbaikan kualitas air dan keberlanjutan ekosistem perairan untuk generasi mendatang.
Lebih lanjut, pentingnya dilakukan perencanaan AMDAL secara matang dan pengelolaan limbah secara bijaksana untuk mencegah terjadinya eutrofikasi. Terdapat beberapa perencanaan yang dapat dilakukan pada proses penapisan (screening) wajib AMDAL. Di antaranya menentukan apakah rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat seperti memberikan informasi tentang rencana kegiatan pembangunan dan dampaknya kepada masyarakat, penyusunan KA-ANDAL meliputi penentuan cakupan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan), serta penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL dengan cara menyusun dan menilai Studi Dampak Lingkungan (ANDAL), Lingkungan Kesehatan (RKL), dan Lingkungan Sosial (RPL).
Daftar Pustaka
Tafangeyasha C, Dzinomwa T. 2005. Land use Impacts on River Water Quality in Lowveld Sand River Systems in South-East Zimbabwe. Land Use and Water Resources Research. 5(3): 3−10.
Kieroger Nasution
Universitas Riau – Sobat Bumi Regional Riau